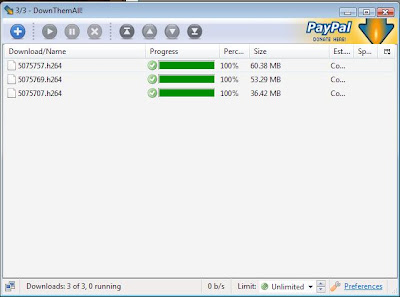Lelaki berambut gondrong itu selalu duduk di pojok kursi Cafe Mawar setiap saya pulang kuliah, sekitar jam lima sore. Entah minuman apa yang ada di depannya, berapa lama dia duduk mendengarkan lagu-lagu yang diputar penjaga cafe, dan apa yang dikerjakannya. saya tidak tahu dan rasanya tidak ingin tahu. Bagi saya, lelaki itu sama saaja dengan pengunjung cafe lainnya yang selalu ada dari pagi sampai malam, sebelum cafe itu tutup pukul sebelas atau dua belas malam.
Saya baru memperhatikan lelaki itu, dan tahu bahwa dia selalu duduk di kursi pojok cafe setiap saya pulang kuliah, ketika Mawarwati yang mengelola cafe bilang bahwa lelaki itu menanyakan saya. Saya tidak tahu, untuk apa dia menanyakan saya, apa kepentingannya, atau bagaimana kelanjutannya. Saya melihatnya sekilas dari jalan, hanya untuk memastikan lelaki mana yang menanyakan saya itu. Setelah tahu, pikiran saya sama sekali tidak memperhatikannya, apalagi Mawarwati yang masih tetangga saya pun tidak pernah membicarakannya lagi.
Sesekali, saat saya melihat ke cafe waktu pulang kuliah, lelaki itu ketahuan memandang saya. Mengapa memandang saya, saya tidak tahu. Sesekali, sesampainya di kamar kos, saya bercermin, memperhatikan penampilan saya, mulai dari baju, celana, hingga rambut. Siapa tahu ada yang tidak wajar.
Penampilan saya, saya rasa, tidak ada yang berlebihan. Rambut saya dipotong pendek. Kadang diikat kalau hari panas. Lipstik dan bedak, tipis saja. Jadi, rasanya tidak ada yang perlu dikawatirkan dengan penampilan saya. Kalaupun lelaki itu memandang saya saat pulang kuliah, saya tidak tahu apakah dia memperhatikan saya sejak di ujung jalan. Tapi itu bukan urusan saya.
Dan, saat lelaki yang kepergok saat memperhatikan saya itu tersenyum dan mengangguk, saya pun membalas tersenyum dan mengangguk. Begitu sampai di kamar kos, tidak ada pikiran tentang dia di kepala saya. Senyuman dan anggukanku tadi hanyalah balasan moral dari seorang manusia yang belajar manusiawi. Rasanya tidak pantas kalau ada orang tersenyum dibalas dengan melengos.
Sesekali saya mendapatkan lelaki itu di taman perumahan, di depan gerbang, sedang menggerak-gerakkan badannya, atau sedang berlari mengelilingi taman, menyusuri jalan kompleks. Saya mengetahuinya bukan dengan semangat memperhatikan. Itu semua saya ingat, karena saya pernah melihat lelaki yang sering duduk di kursi pojok Cafe Mawar dan bisa membedakannya dengan lelaki lain. Selebihnya, tidak ada keinginan mengetahui tentangnya. Dimana dia tinggal, kerja atau kuliah, mengapa rambutnya gondrong, kok selalu sendirian, apakah dia tidak punya keluarga, saya tidak tahu.
Kalau kami berpapasan dia selalu senyum, atau menyapa "hai" dan saya pun menjawab "hai". Saya rasa saya tidak terganggu dengan keramahannya. Perhatian saya masih tetap kepada kuliah, pekerjaan dan kenalan-kenalan saya. Sebulan sekali menulis surat buat orangtua dan adik saya. Waktu senggang saya habiskan buat mendengarkan musik, jalan-jalan atau sesekali nonton.
Kadang Mawarwati masih datang ke kamar kos saya atau saya ke kamarnya. Kami memang bersahabat sejak saya kos di kompleks ini. Dia kuuliah di Sastra, tapi beda kampus dengan saya. Sesekali Mawarwati membicarakan lelaki berambut gondrong itu yang sekarang ada di cafenya. Dari nada bicara Mawarwati saya tidak menangkap ada yang diistimewakan lelaki yang sering menanyakan saya itu. Dia membicarakannya, karena tentang dialah yang diingatnya saat itu. Mawarmati juga membicarakan teman-temannya yanglain yang jago voli atau yang jago main gitar. Tetapi, siapapun yang dibicarakan Mawarwati saya tidak begitu memperhatikannya. saya tidak perduli, dan hanya tersenyum saat Mawarwati menceritakan lelaki yang kadang masih menanyakan saya itu. Katanya, Mawarwati pernah menanyakan mengapa dia tanya saya. Jawab lelaki itu, dia senang saya. Mengapa senang? Lelaki itu tidak menjawab. ia hanya senyum. Mawarwati pun tidak bertanya lagi dengan lelaki itu.
Saya pun tidak menanyakannya. Sekali waktu, saat pulang kuliah, hujan turun. Saya yang baru sampai di gerbang kompleks tidak bisa meneruskan perjalanan. Saya berteduh di depan toko kue. Ke dalam kompleks memang ada angkutan, tapi sedikit. Selain mesti menunggu, waktu-waktu tertentu mesti berebut. Itu pun untuk ke pangkalannya meski jalan kaki sedikit. Jadi, lebih baik berteduh menunggu hujan reda.
Saat itulah saya melihat lelaki itu turun dari bus kota. Dia berlari dan berteduh. Begitu melihat ke arah saya, dia tersenyum dan mendekat. Kami bicara sekadarnya,, tentang hujan dan cuaca, yang akhir-akhir ini sering mendung. Kemudian dia bercerita bahwa Mawarwati sesekali menanyakan, mengapa dia sering memandang saya atau menanyakan tentang saya. Dia menjawab sambil memandang saya dan tersenyum. Katanya, karena dia suka dengan saya. Menurutnyaa rambut saya indah, mata saya bagus, saya ramah, senyum saya susah dilupakan.
Saya tidak menanggapi pernyataannya. Kemudian dia ulurkan tangan, dan bilang mengapa setelah sekian kali jumpa tidak saling kenal. Saya dan dia saling menyebutkan nama. Namanya Gudo. Sebuah nama yang langka.
Saya tidak ingin mengatakan ingatan itu. Perhatian saya kemudian tercuri oleh pertanyaan Gudo yang menginginkan sesekali mengajak saya jalan-jalan menyusuri kompleks ini yang sunyi, mencari buku atau berbincang ala kadarnya. Saya menolak dengan mengatakan, tidak bisa janji karena sibuk. Saat dia menanyakan nomor telepon, karena bisa jadi sekali waktu dia memerlukan saya, saya nyatakaan dengan hati-hati bahwa saya benar-benar sibuk di rumah dan perlu istirahat. Jadi, maaf, saya tidak bisa memberinya nomor telepon.
Selanjutnya pembicaraan kami biasa lagi. Saat azan Magrib berkumandang, hujan belum reda, saya menyatakan akan menembus hujan. Gudo membuka jaketnya, dan memakaikan di tubuh saya. Saya tidak bisa menolak, karena dia terus mengatakan saya lebih pantas memakainya.
Malamnya dia menelpon. Katanya tahu nomor saya dari Maharwati, dan bilang sapu tangan saya tertinggal di kantong jaketnya. Saya ingat-ingat, sapu tangan saya tadi dipakai membersihkan muka memang tanpa sadar saya masukkan ke kantong jaket dan lupa mengambilnya. Gudo janji akan mengembalikannya besok. Kalau diijinkan, dia akan datang ke kost saya. Saya setuju, dan menyatakan akan menunggunya pukul sembilan pagi di Cafe Mawar.
Sekali lagidia bertanya, apakah bisa kalau sesekali mengajak saya jalan-jalan, mencari buku di toko, menonton film, atau menelepon sekedar omong-omong. Saya jawab, mungkin bisa kalau saya tidak sibuk. Mengenai telepon boleh boleh saja, asal tidak terlalu sering dan tahu waktu. Kemudian dia menanyakan kabar saya, apakah saya sudah mandi, makan dan sedang apa sekarang.
Besopknya, begitu saya datang ke Cafe Mawar, sapu tangan itu dititipkan ke Mawarwati. Kata Mawarwati, Gudo tadi menitip sapu tangan, dan tidak pesan apa-apa.
Sejak itu, sehari dua hari, seminggu dua minggu,sampai sebulan saya tidak melihat Gudo dan menerima teleponnya. Mawarwati pun tidak pernah membicarakannya. Saya merasa ada sesuatu yang hilang, entah apa. Atau mungkin itu perasaan saya, karena saya meang tidak mempunyai sesuatu yang hilang.
Pas sebulan lebih seminggu sejak dia mengembalikan sapu tangan saya, Gudo menelepon. Katanya, dia sudah berada di kota lain. Dia ingin menikmati suasana baru. Tapi, katanya, dia tidak bisa melupakan saya, jadi izinkanlah untuk menulis surat setiap kali dia ingat saya. Saya setuju. Seminggu kemudian, surat Gudo datang. Awalnya surat itu bertanggal lama. Katanya sobekan dari buku harian. Isinya: ketertarikannya pada saya, puisi saya. Sebuah puisinya, rasanya mewakili isi catatan catatannya: karena angin daun punya lambai, karena air laut punya biru, karena keluasan langit biru punya sayap, dan karena engkau aku punya rindu.
Dalam pengantarnya, Gudo bilang, sudah terpesona sejak awal melihat saya berjalan pulang kulia. baginya, saya yang berjalan dengan latar belakang matahari senja yang menjingga, lalu tersenyum dan mengangguk, adala pemandangan yang menakjubkan.
Sayang, dia rahu-ragu untuk menyatakannya. jadi, hanya menulisnya di buku harian. Baginya, perasaan seperti itu mesti hati-hati dinyatakan, karena dia tidak pernah menetap di suatu tempat. Sepengalamannya, bila perasaan seperti itu bebas dinyatakan, apalagi dengan kegilaan cinta yang mendebarkan, saat dia mesti pergi untuk menikmati tempat-tempat lain, hanya akan meninggalkan kenangan buruk. tapi, akhirnya dia tidak kuat memendam perasaan seperti itu terus terusan.
Begitu saya menolak seluruh usaha perkenalannya secara halus, Gudo berpikir, barangkali memang benar cinta tidak pantas bagi seorang yang sering pindah-pindah tempat seperti dia. Kalaupun Gudo tidak bisa melupakan saya, menulis di buku harian dan menulis surat, itulah kerahasiaan Tuhan yang menggetarkan. Sekali waktu,dia minta bertemu, berbincang tentang apa saja, dan menikmati senyum saya. "Teruslah tersenyum kepada siapa saja, Putri. Karena, dunia yan gmulai lelah ini butuh senyum seperti milikmu," tulisnya.
Surat surat selanjutnya banyak cerita tentang perjalanannya, peristiwa-peristiwa yang menggetarkan hatinya, pertanyaan-pertanyaan yang menurutnya merupakan kerahasiaan Tuhan. Berbulan-bulan sampai bertahun-tahun saya menerima surat Gudo. Saya menjadi pembacanya yang setia. Sesekali saya pun menulis di buku harian mengomenari suratnya, tentu tidak bisa mengirimkannya buat Gudo karena belum pernah dia menuliskan alamat selain sebuah nama kota di awal setiap suratnya.
Entah sejak kapan saya mulai berpikir untuk membalas suratnya. Sekadar memberi tahu bahwa kuliah saya sudah selesai, dan saya akan pulang ke kota kelahiran. Sebenarnya, saya bisa pindah begitu saja, dan surat suratnya menumpuk atau dikembalikan ke pak Pos. Tapi, diam-diam saya berharap bisa terus membaca surat suratnya. Karena tidak ada alamat Gudo di siapa pun, saya memutuskan untuk mencari kerja di kota ini.
Membaca surat-surat Gudo, saya seperti menyusun sosok seorang lelaki yang selalu khawatir dengan dunia, belajar menyejukkan luka dunia dengan cintanya, dan belajar menyadari bahwa sebagai manusia tidak bisa lepas dari tanah air dan air mata. Entah sejak kapan awalnya, saya menjadi tidak bisa lepas dengan pikiran dan perasaan Gudo. Dia tidak hanya hadir sebagai lelaki yang penuh cinta, tapi juga seperti kerinduan-kerinduan saya yang selam ini tidak pernah saya tahu bagaimana menyusun dan menyatakannya.
Saya mulai mengingat-ingat bagaimana dia tersenyum, menyapa, memberikan jaket saay saya hendak menembus hujan. Barangkali, dulu, bukannya saya tidak memperhatikannya. Tapi, pura-pura tidak perlu dan membutuhkannya. Menikmati surat-surat Gudo yang tidak pernah berhenti mengalir setiap minggu, mungkin akhir hayatnyalah yang bisa memutus catatan-catatannya, saya lupa akan usia. Atau, barangkali, usia tidak mesti ada dalam pikiran seorang menusia yang belajar mencintai apa pun dan siapa pun. Orangtua saya berkali-kali mengingatkan, kapan saya mau menerima lamaran seorang lelaki. Kalau saya tidak punya pilihan, kepada mereka pun banyak yang datang. Tapi, saya tidak lagi berpikir itu.
Entah sejak kapan awalnya saya berharap sekali waktu Gudo datang, tersenyum, dan berbincang tentang luka dunia dan cinta yang meringankan perihnya. Tapi, setiap minggu hanya suratnya yang datang. Saya pun membuat catatan-catatan meresponnay, telh berbuku-buku, entah sampai kapan. Mungkin hidup hanyalah berharap tentang cinta yang abadi, padahal tak lebih dari perjalanan yang akhirnya akan pulang ke tanah air airmata. ***